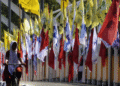MEDIAPARLEMEN – Isu “dinasti politik” di Indonesia masih menjadi bahasan yang menarik. Jika mengacu kepada angota DPR Ri periode 2024-2029, sejumlah kursi di Senayan diketahui diisi oleh figur yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat lain, sehingga memunculkan kekhawatiran akan semakin sempitnya ruang demokrasi di Indonesia.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencatat, sedikitnya 79 dari 580 anggota DPR RI memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat aktif. Angka ini belum termasuk riwayat pekerjaan, proyek bersama, maupun kekerabatan jauh yang sulit dilacak publik.
Pakar Politik dan Demokrasi dari Fisipol UGM, Arga Pribadi Imawan, M.A., menilai fenomena ini merupakan konsekuensi dari sistem partai politik yang masih didominasi lingkaran elit.
“Partai-partai besar hingga hari ini masih dikuasai orang-orang dari lingkar kekuasaan. Posisi strategis sering kali lebih mudah didapatkan karena faktor keluarga atau kerabat, bukan karena kapasitas individu,” ujarnya.
Menurut Arga, setidaknya ada tiga modal yang menentukan seseorang bisa melenggang ke parlemen: modal sosial, modal politik, dan modal ekonomi.
- Modal sosial: popularitas yang biasanya ditopang jejaring keluarga atau status sebagai public figure.
- Modal politik: dukungan kuat dari partai, terutama bagi figur yang mampu menggerakkan mesin politik.
- Modal ekonomi: besarnya biaya kampanye yang kerap menjadi penentu kemenangan.
“Fenomena dinasti politik ini membuat masyarakat biasa semakin sulit masuk ke gelanggang politik,” jelas Arga.
Ia menegaskan, kondisi tersebut akan melanggengkan eksklusivitas di lingkaran politik, sekaligus memperbesar peluang kolusi dan nepotisme. Jika di negara besar seperti Amerika, dinasti politik muncul karena mekanisme demokratis berjalan, maka di Indonesia justru sebaliknya: dinasti politik dianggap melemahkan demokrasi.
Arga juga menyoroti sisi regulasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur larangan keluarga pejabat untuk maju sebagai anggota legislatif. Sementara dalam Pilkada, aturan sempat ada melalui Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2015, namun kemudian dihapus akibat turbulensi politik.
“Selama tidak ada regulasi yang jelas, maka fenomena ini akan terus berulang. Representasi rakyat semakin berkurang karena yang tampil lebih banyak mengabdi pada partai, bukan pada publik,” tegasnya.
Arga berharap kampus dan institusi pendidikan dapat ikut menjaga marwah demokrasi nasional. Caranya, dengan mendorong kajian akademik, diskusi publik, dan penyadaran masyarakat melalui tulisan-tulisan yang kritis. “Universitas punya peran penting untuk mengembalikan demokrasi kita agar tidak terjebak pada lingkaran eksklusif,” tutupnya.